Baca Kembali, Mas Pram
 Pramoedya Ananta Toer, telinga ini belakangan tak asing mendengar namanya. Seorang tokoh pengarang produktif yang mencetuskan sastra sebagai alat perlawanan. Sempat penulis berpikir, mengapa karya sastrawan ini ditawan pemerintah. Buku beliau sempat menghilang, ditelan kekuasaan represif Orde Baru. Padahal jika ditelusuri mendalam, anda akan menemukan semangat revolusioner bangsa Indonesia. Pikirku, mungkin tulisan beliau terlalu kritis sehingga mengancam eksistensi penguasa.
Pramoedya Ananta Toer, telinga ini belakangan tak asing mendengar namanya. Seorang tokoh pengarang produktif yang mencetuskan sastra sebagai alat perlawanan. Sempat penulis berpikir, mengapa karya sastrawan ini ditawan pemerintah. Buku beliau sempat menghilang, ditelan kekuasaan represif Orde Baru. Padahal jika ditelusuri mendalam, anda akan menemukan semangat revolusioner bangsa Indonesia. Pikirku, mungkin tulisan beliau terlalu kritis sehingga mengancam eksistensi penguasa.
Semangat perlawanan, kesan itu pertama aku tangkap. Gagasan segar Mas Pram begitu menggoda. Membaca trilogy Pulau Buru, menyisakan sebuah tanya. Apa kabar Indonesia?. Kau begitu menggoda, jelas itu. Bagaimana tidak, tawaran kekayaan alam sangat berlimpah. Tak habis tujuh turunan, tak heran Belanda bernafsu menjajah. Kita dibuat menderita, kompeni (begitu kita menyebutnya) angkuh menjajah kepuluan Nusantara.
Trilogi Pulau Buru Mas Pram, begitu ia disapa menampilkan Minke. Dalam bukunya Sosok Minke, mengajak kita berwacana mendalam. Sikap kritis dan vocal banyak berbicara. Tulisan pena berisi kalimat perjuangan, sehingga banyak melahirkan pertanyaan. Sekolah tinggi buat apa jika gagal berjuang untuk bangsa. Minke digambarkan sebagai sosok generasi terdidik berjiwa pejuang. Belanda sampai repot dibuatnya, sehingga pengawasan diperketat terhadapnya.
Sesungguhnya membaca trilogy Pulau Buru, tak hanya membaca kata. Makna mendalam perjuangan revolusioner mengajak kita berbicara. Pram, kelihatan menyadari banyak kejahatan pemerintah Belanda selama menjajah. Penderitaan, penyiksaan dan hinaan tak menyurutkan semangat merdeka. Bebas dan merdeka dari penjajahan segala sektor kehidupan.
Penjajahan nilai kemanusiaan, dimana pemerintah Belanda memperbudak rakyat Indonesia. Sistem kerja paksa sangat menyakitkan jika harus dikenang. Ribuan manusia mati, hilang tak berbekas. Selembar nyawa dihargai sangat murah. Bahkan dapat dikatakan, biarkan nyawa satu menghilang selama pembangunan terus berjalan.
Penguasaan Belanda, juga menyiratkan persoalan kemanusiaan. Ada diskriminasi mencolok ketika berbicara masalah hukum. Kaum kulit putih (Belanda) merasa lebih layak berdiri menggagahi kaum pribumi. Ketika permasalahan rumah tangga melanda Minke, sang istri harus mengikuti hukum Belanda. Jasadnya tak layak disemayamkan pada bumi tempat dimana dia ditumbuh kembangkan, Indonesia.
Pendidikan Ala Kompeni
Membaca pendidikan zaman Belanda, sebagaimana terungkap dari novel Pram. Setidaknya saya menemukan kasus pendidikan yang memiriskan hati dan perasaan. Betapa penindasan dan kebodohan sangat dekat dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pendidikan Indonesia mengalami tidur panjang yang menguntungkan penguasa. Ada dua pelajaran penting mengenai pendidikan yang diungkap mas Pram.
Pertama, pendidikan berjalan diskriminatif. Sekolah bagi kaum pribumi hanya menyisakan Sekolah Rakyat (SR). Tak ada kesempatan pribumi, meskipun cerdas menikmati pendidikan lanjutan. Domain pendidikan pasca SR, sudah dikuasai elit pribumi seperti anak bupati. Pendidikan lanjutan dan tinggi (semisal Sekolah Kedokteran), dikuasai anak anak Belanda.
Perbedaan kesempatan mendapatkan pendidikan melahirkan banyak dampak. Masyarakat pribumi dibiarkan makin bodoh demi kelanggengan kekuasaan Gubermen. Pemerintah kolonial berharap kebodohan pribumi, membuat mereka patuh kehendak penguasa. Jika akses pendidikan dibuka, potensi kecerdasan akan merebak di mana mana. Bukan tak mungkin lahir kaum intelektual yang membahayakan kepentingan penjajah Belanda.
Kondisi itu sekarang masih terjadi, pendidikan berjalan diskriminatif. Sekolah dikuasai orang kaya, sedangkan masyarakat miskin kehilangan hak dasarnya, pendidikan. Pemerintah berusaha menampilkan kepedulian semu, semata memancing simpati masyarakat. Sebagai contoh, kasus terbaru terkait adanya Sekolah bertaraf internasional (SBI). Bagaimana mungkin hak pendidikan terus dipelihara sebagai ladang bisnis. Tak ada usaha pemerintah meluruskan kembali pendidikan sebagai kebutuhan mendasar rakyat Indonesia. Ketika sentilan masyarakat mulai popular, pemerintah baru mau turun tangan. Tak untuk membubarkan sekolah bertarif mahal, melainkan merevisi kesalahan yang terlanjur dibiarkan berkembang.
Kedua, pendidikan tak ubahnya doktrin membelokkan pemikiran. Ketika pertama membaca ada perasaan bergejolak melihat arus pemikiran Minke. Dia sangat menganggungkan pemikiran Barat, menyingkirkan pemikiran ke-Timuran. Lebih spesifik, memunculkan kesan mengenyampingkan pemikiran dan gaya hidup Jawa. Kebanggaan sebagai lulusan Barat sangat besar, seakan Barat segalanya.
Kurikulum Barat mendidiknya sebagai manusia masa depan. Pendidikan Barat mendominasi pemikirannya, ironisnya menafikan spirit pemikiran lokal (ke-Indonesiaan). Dalam perkembangannya, arus pemikiran mulai mengalami perubahan. Kondisi gejolak hati dan berbagai episode peristiwa kehidupan membuatnya berpikir ulang. Jawa (pribumi) tak semuanya jumud, Barat tak selamanya buruk. Semua mengalami proses kelebihan dan kekurangan sebagai fitrah dasar kehidupan.
Pendidikan sekarang, mengalami kesalahan yang sama. Benar rasanya berbicara sejarah, fakta serta polanya memungkinkan sama dengan peristiwa dan pelaku berbeda. Lulusan Barat (tanpa bermaksud menggeneralisir) menderita pembelokkan makna. Hampir dapat dikatakan, penguasa pendidikan Indonesia banyak mengadopsi arus pemikiran Barat. Kurikulum pendidikan menyengsarakan masyarakat dan peserta didik. Setiap hari anak Indonesia dijejali padatnya mata pelajaran sehingga tak mengherankan peserta didik tidak fokus.
Kurikulum pendidikan sekarang banyak mengacu pola pendidikan Barat. Sedangkan kebutuhan lokal sebagai budaya timur dipinggirkan. Dampaknya, manusia Indonesia cerdas secara pemikiran, banyak cacat secara moralitas. Ada distorsi memaknai pendidikan, bukan lagi menghasilkan cerdas bermoral. Produk pendidikan Indonesia mengagungkan kecerdasan intelektual, melupakan kecerdasan spiritual dan emosional. Dapat dikatakan pembentukan afektif, psikomotorik dan kognitif berjalan timpang.
Melihat kisah Minke, merevitalisasi pemikiran kita bahwa dunia pendidikan Indonesia mengulang kegagalan. Bagaimana tidak, kesalahan pada masa penjajahan Belanda nyata sekali terulang. Meski konteks peristiwa dan kemasannya berbeda, namun polanya sama. Pendidikan berjalan diskriminatif dan kurikulum yang membodohan peserta didik.
Di masa mendatang, kita sebagai generasi intelektual terdidik perlu merumuskan perubahan. Pendidikan harus mampu diakses semua kalangan masyarakat, murah berkualitas dan kurikulum yang menyenangkan bukan memberatkan. UUD 1945 (versi Amendemen) , Pasal 31, ayat 3 sendiri menegaskan tujuan pendidikan menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang . Jika masih ada diskriminasi pendidikan, artinya pemerintah merampas hak rakyat dan merobek amanat konstitusi.
| Nama | inggar saputra |
| genmuslim_100@yahoo.co.id | |
| Sebagai | Mahasiswa |
| Asal UNIV/Instansi/Daerah | UNJ/JAKARTA |

















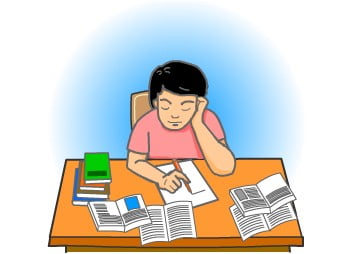
inggar saputra : trus berkarya mas Ikatlah pemikiran dengan tulisan
inggar saputra : trus berkarya mas Ikatlah pemikiran dengan tulisan
good written… sedikit menambahkan saja.. kritikan mengenai kurikulum yang padat dengan berbagai mata pelajaran sudah banyak dikemukakan , bahkan ada penelitian yang menyatakan beratnya beban mata pelajaran telah mencederai otak anak-anak Indonesia.. jika dikatakan konsep pendidikan di Indonesia mengadopsi pemikiran barat memang demikianlah adanya, (tidak bermaksud membela pemerintah nih) tapi sedikit memberikan wawasan saja bahwa setidaknya dalam satu dekade ini kurikulum kita memang mengadopsi pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP yang merupakan keturunan dari mazhab Behaviorisme dan dijadikan sebagai landasaran dalam "kurikulum transmisi" dalam pendidikan.. jika ditilik dari sejarahnya model kurikulum ini berkembang karena pada masa itu (abad 19) di dunia barat faktor ekternal persekolahan pengaruhnya sangat memprihatinkan khususnya bagi peserta didik, faktor2 tersebut adalah media masa (koran), kondisi politik, dan sebagainya.. kondisi ini mendorong para pemikir pendidikan pendukung mazhab behaviorisme untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menangkal semua dampak negatif dari media-media informasi yang berkambang saat itu. mereka (ahli) menyimpulkan bahwa perhatian peserta didik harus dialihkan dari faktor eksternal tersebut salah satunya adalah mengarahkan perhatian peserta didik pada muatan-muatan mata pelajaran, menjadikan buku sebagai satu2nya sumber ilmu pengetahuan dan guru sebagai garda terdepan penyampai knowledge yang ada dalam buku2 tersebut. pertanyaannya, apakah Indonesia saat ini cocok jika menggunakan kurikulum transmisi yang salah satu cirinya memiliki banyak muatan mata pelajaran? tentu saja jawabannya harus kita kaitkan antara kondisi lahirnya kurikulum ini dengan kondisi faktor eksternal yang terjadi di Indonesiaa saat ini yg sangat berpengaruh terhadap peserta didik, contoh faktor eksternal tersebut: pemberitaan media masa saat ini, tayangan sinetron di televisi, jaringan internet tanpa batas, kasus-kasus amoral selebritis, infotainment dan sebagainya… monggo ditelaah kembali…diskriminatif dalam bidang pendidkan juga perlu dicermati dari ranah mana yang harus kita kritisi, dan ranah mana yang harus diperbaiki, mengingat dalam renstra pendidikan nasional salah satunya disebutkan mengenai pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai salah satu perwujudan dari amanat UUD 1945. apakah ini hanya sekedar cari muka ataukah memang benar2 program pro rakyat? karena saya bukan orang politik saya tidak bisa menjawabnya, karena baik dan buruk jika dilihat secara politik akan menjadi berbeda…. setidaknya renstra tersebut telah menunjukkan niatan baik dari pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan tanpa diskriminatif.. Kenapa terjadi penyimpangan? itu yang harus dikritisi… contohnya BOS, jika dilaksanakan tanpa penyimpangan rakyat Indonesia akan menikmati indahnya bersekolah, kalau mau jujur penyimpangan mulai terjadi di tingkat kabupaten ke bawah, karena pemerintah pusat tidak memotong sedikitpun uang BOS tersebut, yg perlu dipikirkan bagaimana memperbaiki kondisi ini yang merupakan konsekuensi dari OTDA (otonomi daerah atau otak dagang ya)… RSBI juga amanat undang2, kenapa harus disalahkan? kalau SBI itu menyebabkan anak harus membayar lebih tinggi saya kira sekolahnya saja yang lebay, karena mereka sama sekali tidak menunjukkan korelasi antara biaya dan mutu.. bahkan tidak konsekuen dengan standar internasionalnya.. karena mereka tidak ada bedanya dengan sekolah negeri pada umumnya. kalau alasannya untuk kesejahteraan guru, terus untuk apa ada sertifikasi guru dan gaji profesinya? bisa dilihat kan siapa yang akal2an memahalkan biaya sekolah… saya kira jika lulusan PLS bisa membuat PKBM Berstandar Internasional dengan biaya murah hal ini akan menjadi pukulan telak bagi mereka yang membuat RSBI menjadi mahal bahkan mungkin bisa mendorong pemerintah untuk merubah kebijakannya…saya kira itu saja tanggapannya… sekali lagi tidak bermaksud membela pemerintah ini semata karena berbagai hal yang telah saya pelajari dan dianalisis, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. learning can be on facebook…. PLS banget deh pokoknya…
good written… sedikit menambahkan saja.. kritikan mengenai kurikulum yang padat dengan berbagai mata pelajaran sudah banyak dikemukakan , bahkan ada penelitian yang menyatakan beratnya beban mata pelajaran telah mencederai otak anak-anak Indonesia.. jika dikatakan konsep pendidikan di Indonesia mengadopsi pemikiran barat memang demikianlah adanya, (tidak bermaksud membela pemerintah nih) tapi sedikit memberikan wawasan saja bahwa setidaknya dalam satu dekade ini kurikulum kita memang mengadopsi pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP yang merupakan keturunan dari mazhab Behaviorisme dan dijadikan sebagai landasaran dalam "kurikulum transmisi" dalam pendidikan.. jika ditilik dari sejarahnya model kurikulum ini berkembang karena pada masa itu (abad 19) di dunia barat faktor ekternal persekolahan pengaruhnya sangat memprihatinkan khususnya bagi peserta didik, faktor2 tersebut adalah media masa (koran), kondisi politik, dan sebagainya.. kondisi ini mendorong para pemikir pendidikan pendukung mazhab behaviorisme untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menangkal semua dampak negatif dari media-media informasi yang berkambang saat itu. mereka (ahli) menyimpulkan bahwa perhatian peserta didik harus dialihkan dari faktor eksternal tersebut salah satunya adalah mengarahkan perhatian peserta didik pada muatan-muatan mata pelajaran, menjadikan buku sebagai satu2nya sumber ilmu pengetahuan dan guru sebagai garda terdepan penyampai knowledge yang ada dalam buku2 tersebut. pertanyaannya, apakah Indonesia saat ini cocok jika menggunakan kurikulum transmisi yang salah satu cirinya memiliki banyak muatan mata pelajaran? tentu saja jawabannya harus kita kaitkan antara kondisi lahirnya kurikulum ini dengan kondisi faktor eksternal yang terjadi di Indonesiaa saat ini yg sangat berpengaruh terhadap peserta didik, contoh faktor eksternal tersebut: pemberitaan media masa saat ini, tayangan sinetron di televisi, jaringan internet tanpa batas, kasus-kasus amoral selebritis, infotainment dan sebagainya… monggo ditelaah kembali…diskriminatif dalam bidang pendidkan juga perlu dicermati dari ranah mana yang harus kita kritisi, dan ranah mana yang harus diperbaiki, mengingat dalam renstra pendidikan nasional salah satunya disebutkan mengenai pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai salah satu perwujudan dari amanat UUD 1945. apakah ini hanya sekedar cari muka ataukah memang benar2 program pro rakyat? karena saya bukan orang politik saya tidak bisa menjawabnya, karena baik dan buruk jika dilihat secara politik akan menjadi berbeda…. setidaknya renstra tersebut telah menunjukkan niatan baik dari pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan tanpa diskriminatif.. Kenapa terjadi penyimpangan? itu yang harus dikritisi… contohnya BOS, jika dilaksanakan tanpa penyimpangan rakyat Indonesia akan menikmati indahnya bersekolah, kalau mau jujur penyimpangan mulai terjadi di tingkat kabupaten ke bawah, karena pemerintah pusat tidak memotong sedikitpun uang BOS tersebut, yg perlu dipikirkan bagaimana memperbaiki kondisi ini yang merupakan konsekuensi dari OTDA (otonomi daerah atau otak dagang ya)… RSBI juga amanat undang2, kenapa harus disalahkan? kalau SBI itu menyebabkan anak harus membayar lebih tinggi saya kira sekolahnya saja yang lebay, karena mereka sama sekali tidak menunjukkan korelasi antara biaya dan mutu.. bahkan tidak konsekuen dengan standar internasionalnya.. karena mereka tidak ada bedanya dengan sekolah negeri pada umumnya. kalau alasannya untuk kesejahteraan guru, terus untuk apa ada sertifikasi guru dan gaji profesinya? bisa dilihat kan siapa yang akal2an memahalkan biaya sekolah… saya kira jika lulusan PLS bisa membuat PKBM Berstandar Internasional dengan biaya murah hal ini akan menjadi pukulan telak bagi mereka yang membuat RSBI menjadi mahal bahkan mungkin bisa mendorong pemerintah untuk merubah kebijakannya…saya kira itu saja tanggapannya… sekali lagi tidak bermaksud membela pemerintah ini semata karena berbagai hal yang telah saya pelajari dan dianalisis, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. learning can be on facebook…. PLS banget deh pokoknya…
sangat inspiratif tuks buat kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat PLS, sekecil apapun kita harus berbuat seperti pramudya yg menyuarakan fakta dan data yang diolah jadi menarik…..
sangat inspiratif tuks buat kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat PLS, sekecil apapun kita harus berbuat seperti pramudya yg menyuarakan fakta dan data yang diolah jadi menarik…..
SBI DALAM bidang formal hanya membuat kesenjangan dalam dunia pendidikan,,hanya karena SBI peserta didik dalam lingkup formal yang miskin menjadi kumpul dalam 1 kotakan, mereka hanya masuk disekolah pinggiran dan mendapat anggaran pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan sekolah SBI,,,hal tersebut berdampak semakin melangenggkan ketidak adilan dalam masyarakat sekaligus merusak solidaritas sosial…sedangkan dalam PLS kelemahan kita adalah masih belum diperhatikannya PLS dalam dunia pendidikan, selain itu masih kurangnya pengetahuan dan kreativitas para mahasiswa serta pamong belajar yang kurang kreatif,,hemmm coba deh kita mencoba inovasi model pembelajaran yang baru untuk PLS…pasti itu akan dasyad,,HIDUP PLS.._SALAM DARI SAYA PLS UNY 2008 _
SBI DALAM bidang formal hanya membuat kesenjangan dalam dunia pendidikan,,hanya karena SBI peserta didik dalam lingkup formal yang miskin menjadi kumpul dalam 1 kotakan, mereka hanya masuk disekolah pinggiran dan mendapat anggaran pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan sekolah SBI,,,hal tersebut berdampak semakin melangenggkan ketidak adilan dalam masyarakat sekaligus merusak solidaritas sosial…sedangkan dalam PLS kelemahan kita adalah masih belum diperhatikannya PLS dalam dunia pendidikan, selain itu masih kurangnya pengetahuan dan kreativitas para mahasiswa serta pamong belajar yang kurang kreatif,,hemmm coba deh kita mencoba inovasi model pembelajaran yang baru untuk PLS…pasti itu akan dasyad,,HIDUP PLS.._SALAM DARI SAYA PLS UNY 2008 _